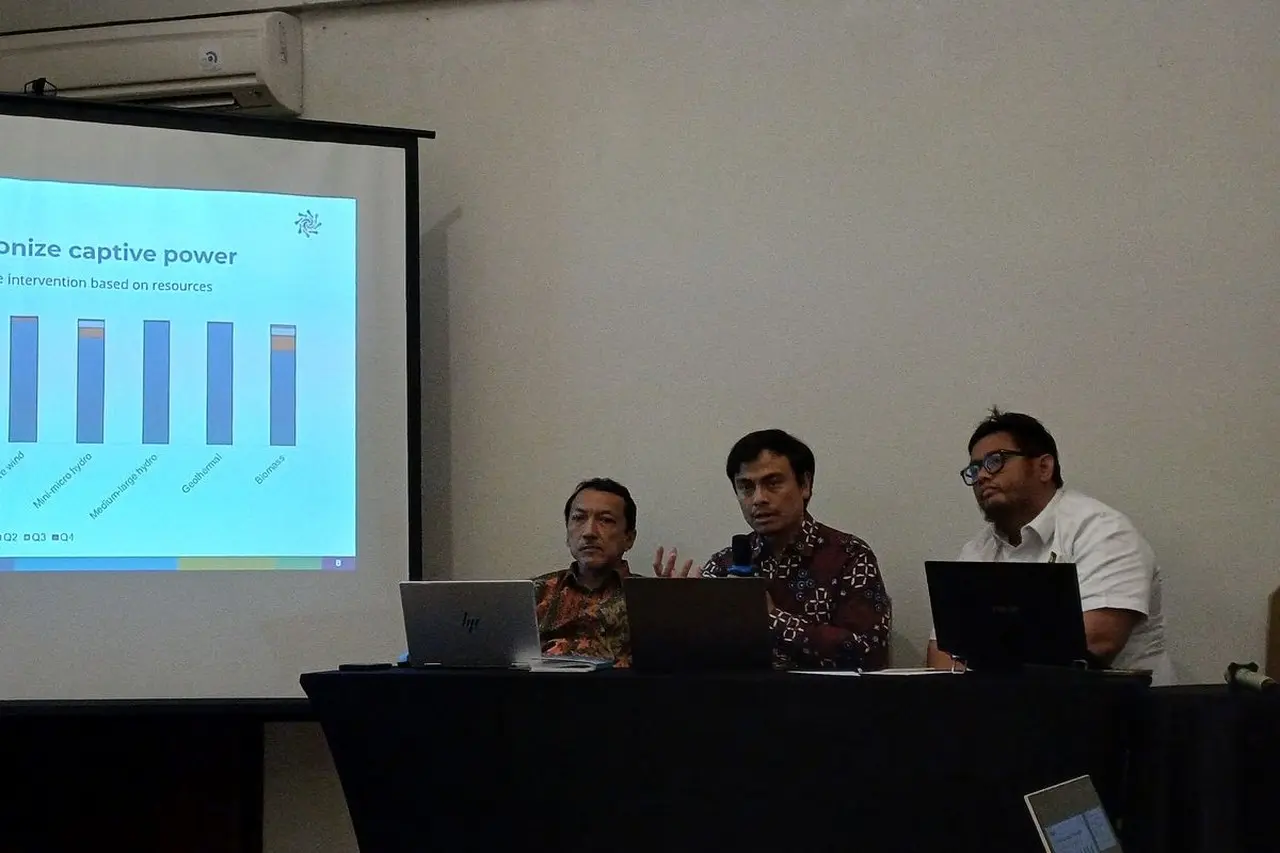Pertumbuhan pembangkit listrik mandiri atau captive power plant di sektor industri Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperingatkan bahwa dominasi pembangkit berbasis fosil ini berisiko menghambat transisi energi bersih dan menekan daya saing produk ekspor nasional di pasar global.
Lonjakan Kapasitas Pembangkit Listrik Industri
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kapasitas pembangkit listrik captive di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data IESR, kapasitas yang semula hanya 14 gigawatt (GW) pada 2019 melonjak drastis menjadi 33 GW pada 2024.
Tren ini diprediksi akan terus berlanjut dengan adanya tambahan 17,4 GW dalam pipa proyek setelah tahun 2024. Saat ini, sekitar 5 GW pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan 2,5 GW pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sudah memasuki tahap konstruksi untuk memenuhi kebutuhan industri padat energi seperti smelter nikel, aluminium, dan baja.
Risiko Emisi dan Jebakan Energi Kotor
Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menyatakan bahwa ketergantungan pada energi fosil ini dapat menjebak industri dalam penggunaan energi kotor untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia sulit beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
“Apabila tidak dikendalikan, pembangkit listrik captive berbasis fosil ini bisa membuat Indonesia susah pindah ke energi yang lebih bersih, dan bisa terjebak pakai energi kotor itu lama sekali, sampai puluhan tahun ke depan,” ujar Raditya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Pada tahun 2024, emisi dari pembangkit listrik mandiri ini tercatat mencapai 131 MtCO2, atau menyumbang sekitar 37 persen dari total emisi sektor ketenagalistrikan. Jika pertumbuhan ini dibiarkan tanpa kendali, emisi karbon diperkirakan akan membengkak hingga 166 MtCO2 pada tahun 2037.
Ancaman Terhadap Daya Saing Ekspor
Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat Uni Eropa akan mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan tersebut akan mengenakan biaya karbon pada produk impor dengan intensitas emisi tinggi. Saat ini, produk aluminium dan baja Indonesia memiliki intensitas emisi 45,5 persen hingga 89,9 persen lebih tinggi dibandingkan standar Uni Eropa.
Raditya menambahkan bahwa pelaku industri sebenarnya memahami urgensi dekarbonisasi, namun keputusan investasi masih didominasi oleh pertimbangan biaya jangka pendek. Tanpa adanya sinyal harga karbon yang kuat atau regulasi yang tegas, energi terbarukan seringkali dianggap belum optimal secara finansial bagi pelaku usaha.
Informasi lengkap mengenai isu dekarbonisasi industri ini disampaikan melalui pernyataan resmi IESR dalam acara bertajuk “Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Indonesia” yang dirilis pada 19 Februari 2026.